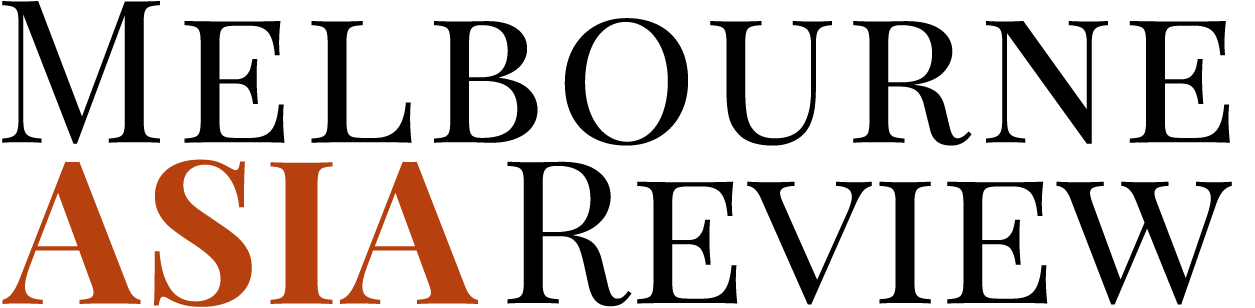Penggunaan kekerasan oleh kelompok-kelompok seperti preman jalanan, gangster, vigilante, laskar dan paramiliter — atau disebut juga sebagai privatised violence — selalu menyertai perkembangan negara di Indonesia.
Sejak demokratisasi tahun 1998, kelompok semacam ini begitu banyak bermunculan. Sebagian besar di antara mereka memberi perhatian pada upaya penegakan moralitas Islam mewujudkan doktrin amar ma’ruf nahi munkar (menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran). Sebelumnya, pada era otoriter Suharto, mereka umumnya mengusung sentimen nasional dan mengklaim sebagai pembela Pancasila.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, memandang Islamisasi kelompok-kelompok kekerasan ini adalah indikasi menguatnya militansi Islam. Lebih jauh, Jones bahkan berargumen bahwa vigilante Islam dapat menjadi tempat yang melahirkan para jihadis, kelompok Muslim militan yang bertujuan mendirikan negara Islam menggunakan kekerasan.
Namun, analisis pendekatan sekuriti semacam itu umumnya didasarkan pada ketakutan berlebihan dan cenderung membesar-besarkan fakta mengenai penggunaan identitas Islam oleh kelompok kekerasan. Padahal, bagi sebagian besar kelompok kekerasan, mengusung sentimen Islam sekadar taktik merespons ekologi sosial baru yang telah menempatkan Islam sebagai sumber mobilisasi yang efektif. Hasil penelitian studi doktoral saya di Asia Institute, University of Melbourne menemukan bahwa penggunaan retorika Islam oleh preman jalanan hanyalah cara untuk memperkuat posisi mereka dalam praktik pemerasan dan dalam membangun aliansi predatoris dengan elite politik.
Kelompok-kelompok kekerasan ini telah menunjukkan bagaimana mereka terus bergantung membangun hubungan patronase dengan elite politik, ketimbang telah menjadi semakin otonom seperti yang diklaim oleh para peneliti yang menggunakan perspektif institusional. Menurut perspektif ini, demokrasi yang terdesentralisasi di Indonesia telah mengubah pola patronase politik dan membuat negara menjadi semakin terfragmentasi serta kehilangan kontrolnya terhadap kelompok-kelompok kekerasan. Pandangan demikian menganggap kelompok ini tidak lagi punya legitimasi formal karena lepasnya kendali yang terpusat oleh negara; para vigilante yang semakin otonom itu mengartikulasi identitas dan retorika Islam sebagai cara baru untuk membuat penggunaan kekerasan tetap sahih. Namun, seperti akan saya tunjukkan di bawah, Islamisasi para gangster justru mengonfirmasi yang sebaliknya bahwa ketimbang menjadi semakin otonom mereka terus bergantung pada elite ekonomi-politik untuk bertahan.
Menguatnya Konservatisme Islam
Menjamurnya kelompok preman Islam di Indonesia pasca-otoritarianisme mesti dipahami dalam konteks menguatnya konservatisme Islam yang illiberal dan anti-pluralis. Tendensi menguatnya konservatisme Islam ditandai oleh semakin pentingnya kedudukan Islam memainkan peran dalam kehidupan sosial-kultural, meski tidak berarti hal itu diikuti oleh formalisasi Islam dalam lembaga-lembaga negara.
Sebab, kelompok Muslim konservatif di Indonesia sangat terfragmentasi – tidak ada kendaraan politik yang layak dan koheren yang dapat merepresentasikan berbagai kepentingan mereka. Dalam memperjuangkan kepentingannya, kelompok konservatif menjadi amat bergantung pada para politisi, termasuk yang sekuler sekalipun. Sebaliknya, para politisi sekuler juga sangat berkepentingan membangun aliansi dengan Muslim konservatif untuk memobilisasi suara mereka dalam kompetisi elektoral. Akibatnya, konservatisme Islam tetap marginal secara politik, tetapi ia telah menjadi sumber mobilisasi sosial-politik baru yang amat efektif. Preman, gangster, kelompok vigilante dan semacamnya karena itu telah beralih dari yang semula sebagai pembela Pancasila menjadi pembela ekspresi-ekspresi Islam konservatif.
Patut dicatat, menguatnya konservatisme Islam mesti dipahami lebih dari sekadar ekspresi sosial-kultural semata. Ia juga respons atas meningkatnya kerentanan ekonomi dan kekecewaan politik, manifestasi atas apa yang disebut oleh para sarjana seperti Vedi Hadiz dan Angelos Chryssogelos sebagai ‘pengingkaran janji-janji modernitas’. Dalil modernitas mengandaikan bahwa hadirnya industrialisasi akan memperbesar jumlah kelas menengah terdidik yang menjadi tulang punggung lahirnya masyarakat sekuler dan politik demokrasi yang liberal.
Dalam banyak kasus, seperti di Indonesia, modernitas pada kenyataannya justru menghasilkan kecemasan sosial-ekonomi. Menurut catatan World Bank, jumlah kelas menengah Indonesia memang membesar dari 25 persen dari total populasi pada tahun 1999 menjadi 65 persen pada tahun 2020, namun 69 persen darinya tergolong sebagai kelompok yang baru beranjak menjadi kelas menengah (aspiring middle class). Mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi rentan jatuh kembali menjadi kelas bawah, terutama jika terjadi krisis.
Alih-alih mengusung sekularisasi, banyak kelas menengah Muslim justru berpaling pada agama dan mendorong Islamisasi ruang publik dalam upaya mengatasi kecemasan sosial-ekonomi mereka. Beberapa sarjana seperti Alejandro Colás juga telah mengidentifikasi aspek lain yang memungkinkan menguatnya konservatisme Islam itu, yakni terkait ketiadaan gerakan kiri. Di Indonesia, politik kiri telah begitu lemah jika tidak bisa dibilang absen sejak pembantaian komunis tahun 1965. Karena tidak adanya alternatif, konservatisme Islam menjadi artikulasi dominan dari kecemasan sosial-ekonomi dan kekecewaan politik kelas menengah Muslim.
Tren semakin konservatifnya kelas menengah Muslim Indonesia ini dapat diamati di antaranya dari meningkatnya konsumsi komoditas-komoditas Islam, produk-produk sosial-ekonomi yang mereprentasikan kesalehan. Indikator lainnya dapat dilihat dari adanya fenomena hijrah, terutama dari kalangan anak muda yang mengekspresikan ketaatan dalam beragama, tampak di antaranya dari cara mereka berpakaian. Perumahan kluster khusus Muslim juga semakin populer sebagaimana juga penggunaan jasa bank syariah, pendidikan Islam dan konsumsi obat herbal Islami.
Islamisasi kelompok-kelompok kekerasan adalah respons atas tren menguatnya konservatisme Islam itu. Penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa mereka mengartikulasikan identitas dan retorika Islam seperti amar ma’ruf nahi munkar untuk memperkuat pengaruh dalam premanisme dan dalam upaya membangun aliansi dengan elite ekonomi-politik.
Taktik Memperkuat Pengaruh, bukan Jalan Menuju Jihadisme
Pengamat terorisme seperti Sidney Jones mengklaim bahwa kelompok preman Islam telah bertransformasi dari sekadar organisasi yang berupaya menegakkan moralitas Islam menjadi sumber perekrutan teroris. Menurutnya, aksi-aksi sweeping berbagai tempat dan aktivitas yang dianggap maksiat dalam rangka nahi munkar serta intimidasi terhadap kelompok minoritas agama menjadi medium untuk bertransformasi sebagai jihadis, yang pada akhirnya mengaburkan batas antara kelompok vigilante Islam dan teroris.
Padahal, banyak anggota kelompok preman Islam tidak memiliki pemahaman keagamaan yang memadai. Jika pun mereka mengklaim bercita-cita mendirikan negara Islam, hal itu dilakukan untuk memperkuat pengaruh dalam premanisme. Sedikit sekali bukti yang mengindikasikan adanya transformasi dari kelompok preman menjadi organisasi teroris.
Tim Hisbah (kelompok preman Islam yang paling berpengaruh di Solo pada akhir tahun 2000-an), adalah satu-satunya organisasi yang diklaim telah mengalami transformasi itu. Berdasarkan laporan kepolisian, anggota Tim Hisbah terlibat dalam beberapa aksi bom bunuh diri di Solo dan Cirebon, Jawa Barat, yang pada akhirnya membuat grup ini menjadi target satuan khusus kepolisian anti-terorisme, Densus 88.
Laporan International Crisis Group (ICG) tahun 2012 juga menyatakan bahwa Tim Hisbah telah menjadi kelompok teroris pada tahun 2010 setelah pemimpinnya Sigit Qordhowi mengekspresikan simpatinya pada Abu Bakar Ba’asyir, salah satu tokoh jihadis paling berpengaruh di Indonesia. Sigit juga dilaporkan telah berencana menyerang polisi setelah salah satu anggota Tim Hisbah tewas dalam operasi anti-terorisme di Sumatera Utara. Tahun 2011, Sigit dan anggota Tim Hisbah lainnya Hendro Yunianto tewas tertembak setelah disergap polisi anti-teror di Solo. Anggota lainnya dari organisasi ini ditangkap atas tuduhan pemilikan senjata api dan keterlibatan dalam rencana penyerangan polisi.
Akan tetapi, berbagai hasil wawancara penelitian saya menunjukkan bahwa kelompok preman Islam seperti Tim Hisbah sangat mungkin mengasosiasikan diri mereka sebagai kelompok teroris dan bersimpati pada tokoh-tokoh jihadis, tapi hal ini umumnya dilakukan untuk meningkatkan derajat intimidasi dalam aksi premanisme. Sigit dan anggota Tim Hisbah lainnya hampir tidak pernah menerima pendidikan Islam yang intensif, tapi menemukan Islam sebagai perangkat yang sangat berguna untuk mendukung aksi premanisme seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya seperti Kalono dan Yanni Rusmanto yang terlibat dalam premanisme Islam tetapi tidak dalam jihadisme.
Kalono dengan Front Pembela Islam Surakarta (FPIS)-nya dan Yanni dengan laskar Hisbullah-nya mendominasi dunia preman di Solo pada awal tahun 2000-an yang kerap melakukan aksi-aksi anti-kemaksiatan. Pada pertengahan tahun 2000-an, keduanya semakin jarang menggunakan kelompok preman Islam dan narasi anti-kemaksiatan setelah aktivitas bisnisnya dengan anggota polisi dan militer — baik yang legal maupun ilegal — semakin mapan. Hal ini membuka ruang bagi Sigit mengambil alih kontrol atas dunia preman di Solo menggunakan retorika Islam. Ia beberapa kali mendirikan kelompok vigilante Islam, termasuk di antaranya Tim Hisbah, pada tahun 2008. Bagi seorang tokoh seperti Sigit, penggunaan narasi dan identitas Islam yang instrumental dalam aksi premanisme bukanlah tanda telah terjadinya transformasi radikal dari vigilantisme ke terorisme seperti klaim para ahli teroris dan pendekatan sekuriti.
Penting pula dicatat, pengakuan para tersangka yang dibuat selama proses interogasi oleh kepolisian – yang menjadikan Tim Hisbah pada akhirnya dikategorikan sebagai kelompok teroris – dapat sangat menyesatkan karena jamaknya penggunaan siksaan dan intimidasi dalam proses itu. Ahli politik John Sidel mengemukakan bahwa banyak pengamat teroris membuat gambaran mengenai ancaman Islam politik secara berlebihan karena mendasarkan analisisnya terutama pada sumber-sumber resmi institusi keamanan yang dapat sangat diragukan kebenarannya.
Seorang anggota Tim Hisbah, Edy Jablay, yang dipenjara tak lama setelah tewasnya Sigit mengklaim bahwa ia memperoleh siksaan dan ancaman dari aparat kepolisian selama proses interogasi. Dalam wawancara yang saya lakukan kepadanya (21 Oktober, 2016), ia mengatakan:
Intimidasi selama proses interogasi itu sudah biasa. Saya disiksa oleh polisi. Di antara anggota Tim Hisbah lainnya, saya memperoleh perlakukan yang paling buruk. Yang lain dengan mudah mengakui setelah beberapa kali dipukul. Saya tidak. Saya disetrum. Saya merasa ada benda tajam ditusukkan di pembuluh darah dan di kaki saya, tidak lama kemudian disetrum. Mulut saya diplester, mata saya ditutup, sedangkan tangan saya diborgol di belakang dan kaki saya dirantai. Saya dipaksa mengakui bahwa saya terlibat dalam merencanakan aksi terorisme, bahwa saya adalah teroris karena pandangan ideologis saya tentang Islam.
Edy juga mengatakan bahwa ia dipaksa mengaku bahwa ia merencanakan aksi terorisme, menyerang polisi dan bahwa hal itu terkait pandangannya tentang Islam dan negara Indonesia.
Saya bisa menerima dihukum karena pemilikan senjata api, tapi tidak atas pandangan saya tentang Islam atau tentang negara Indonesia. Pandangan-pandangan itu tidak bisa dihukum. Banyak teman saya yang tidak terlibat dalam pemilikan senjata api, tapi karena menghadiri pengajian yang sama di Tim Hisbah, mereka juga dipenjarakan dan dihukum. Mereka dipaksa dan diarahkan agar mengakui bahwa Syariah Islam adalah wajib dan bahwa negara Indonesia adalah kafir. Pada akhirnya mereka menerima hukuman yang bahkan lebih tinggi dari saya.
Edy juga mengklaim bahwa Tim Hisbah bukanlah kelompok teroris; ia tidak lebih dari sekadar kelompok yang berjuang menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Ia juga mengaku bahwa memang banyak anggota Tim Hisbah yang sering ikut dalam pengajian yang menghadirkan Abu Bakar Ba’asyir dan Aman Abdurrahman, tapi semua kegiatan itu terbuka untuk publik tanpa ada yang disembunyikan dari otoritas karena acara dan pandangan-pandangan yang dikemukakan tidak berkaitan dengan terorisme. Edy juga mengakui bahwa ia memiliki senjata api ilegal, tapi menurutnya senjata itu hanya akan digunakan sebagai upaya bela diri menghadapi kemungkinan serangan dari polisi.
Setelah terbunuhnya Sigit, Tim Hisbah kemudian lenyap dalam dunia premanisme Islam di Solo seperti yang juga telah terjadi pada kelompok preman lainnya. Tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok baru kemudian bermunculan seperti Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang dipimpin oleh Edi Lukito, yang kini mendominasi aksi-aksi anti-kemaksiatan di Solo menggunakan narasi yang sama seperti Tim Hisbah.
Kelompok Preman Islam tetap Marginal dalam Arena Politik
Sejauh ini, kelompok preman Islam telah sangat aktif terlibat dalam kontestasi kekuasaan sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensinya, ketimbang mendukung jihadisme. Mobilisasi retorika Islam bukan hanya untuk memperkuat pengaruhnya di jalanan, tapi juga untuk membangun aliansi dengan para politisi.
Pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017, misalnya, kelompok laskar Islam yang paling terkenal di Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), berperan paling menonjol dalam memobilisasi sentimen Islam menyerang kandidat petahana – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang memiliki status minoritas ganda sebagai Cina non-Muslim – dengan tuduhan penodaan agama. Ratusan ribu Muslim konservatif berpartisipasi dalam rangkaian demonstrasi yang dipimpin oleh FPI. Tidak lama setelah demonstrasi pertama, lawan-lawan politik Ahok – yang selama ini berupaya menunjukkan dirinya tidak terasosiasi dengan FPI karena citranya sebagai kelompok kekerasan – mengklaim bahwa mereka mendukung aksi-aksi protes itu.
Namun demikian, patut dicatat bahwa kelompok preman Islam semacam FPI mungkin saja telah memainkan peran penting dalam kontestasi kekuasaan, seperti memobilisasi suara dari kalangan Muslim konservatif, tapi sesungguhnya mereka secara politik tetap marginal. Aliansi antara FPI, kalangan Muslim konservatif dan para politisi oportunis memang telah membuat Ahok kandidat petahana yang popularitasnya tinggi itu kalah dalam kontestasi kekuasaan dan sekaligus dipenjara dengan pidana penodaan agama. Representasi dari aliansi ini, Anies Baswedan, adalah yang kemudian memenangkan kontestasi itu, tapi ia sejauh ini tidak membuat atau mengimplementasikan kebijakan bernuansa Islam yang memfasilitasi kepentingan Muslim konservatif itu. Bahkan, pada pemilihan presiden tahun 2019, Muslim konservatif dicampakkan begitu saja oleh politisi sekuler oportunis. Kelompok konservatif ini mendukung Prabowo Subianto, tetapi aliansi ini kalah dan tak lama kemudian Prabowo meninggalkan mereka dan beralih mendukung rivalnya Presiden Jokowi.
Dengan demikian, Islamisasi kelompok-kelompok kekerasan tidak membuat mereka menjadi teroris dan mereka juga tidak menjadi sumber perekrutan para jihadis baru. Alih-alih berpartisipasi dalam terorisme, anggota kelompok preman Islam telah menjadi lebih aktif dalam arena politik formal dalam upaya membangun aliansi dengan para politisi. Islamisasi kelompok-kelompok kekerasan juga menunjukkan bahwa mereka tetap bergantung pada hubungan-hubungan patronase dengan elite politik, ketimbang menjadi lebih otonom, untuk mempertahankan eksistensinya.
Tulisan ini diterjemahkan oleh Abdil Mughis Mudhoffir dari “Indonesian vigilantes are voicing a conservative Islam, but they are not becoming terrorists” yang dimuat di jurnal online Melbourne Asia Review edisi 4, 11 November 2020 (DOI: https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X4.21) dengan sejumlah penyuntingan. Penerjemahan dan penerbitan di NU Online seizin penulis dan penerbit.
Image: Lascar of Islamic Ummah of Surakarta, Solo, Central Java, 2016. Credit: Author.